Cerita Budak Lembur
Blog ini berisi tentang curahan hati orang lembur
Jumat, 16 Desember 2011
MOTO DAN KUTIPAN
18 Juli 2009
Motto:
Seseorang harus melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, selebihnya kita pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan menyimpan hambatan dan kegagalan dalam hati, karena kita harus menguasai hambatan dan rintangan hidup. Bukan sebaliknya di dukung oleh kesulitan hidup.
KUTIPAN
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu
Ada kemudah...
Seseorang harus melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, selebihnya kita pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan menyimpan hambatan dan kegagalan dalam hati, karena kita harus menguasai hambatan dan rintangan hidup. Bukan sebaliknya di dukung oleh kesulitan hidup.
KUTIPAN
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu
Ada kemudah...
Kamis, 15 Desember 2011
Darso - Kahayang keukeuh
Mimitina iseng
kureuseup ngaheureuyanna
Geugeut ka geulisna
Gereget kan bodina
Tina iseng kalah manteung
tina heureuy asup kana hate
tungtungna kuring bebeakan
Ngabelaan nganjuk ngahutang
mahugi hayang kapake
lindeuk - lindeuk japati
rek dicium mah hararese
Usaha anu can hasil
kaburu beakeun modalna
rek ngalamar teu boga duit
Kuring nu ngoleang
manehna kabandang batur
cinta nu kapakan
hate kuring kakalayangan
Kahayang teu kahontal
manehna kawin jeung batur
hate anu peurih
ceurik ceurik ku nalangsa
Duriat pageuh
kahayang keukeuh
ngalamun teu paruguh
nunggu randana
kureuseup ngaheureuyanna
Geugeut ka geulisna
Gereget kan bodina
Tina iseng kalah manteung
tina heureuy asup kana hate
tungtungna kuring bebeakan
Ngabelaan nganjuk ngahutang
mahugi hayang kapake
lindeuk - lindeuk japati
rek dicium mah hararese
Usaha anu can hasil
kaburu beakeun modalna
rek ngalamar teu boga duit
Kuring nu ngoleang
manehna kabandang batur
cinta nu kapakan
hate kuring kakalayangan
Kahayang teu kahontal
manehna kawin jeung batur
hate anu peurih
ceurik ceurik ku nalangsa
Duriat pageuh
kahayang keukeuh
ngalamun teu paruguh
nunggu randana
sumber : http://liriksunda.blogspot.com/2009/11/kahayang-keukeuh-darso.html#ixzz1gcHvP9zW
helikopter
Helikopter bisa naik ke atas karena ada gaya angkat yang dihasilkan oleh baling-baling helikopter. Prinsip baling-baling ini sama dengan prinsip sayap pesawat pada umumnya.
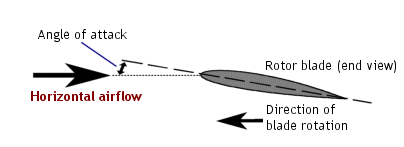
Ketika dilihat dari samping, bentuk bilah baling-baling helikopter akan tampak seperti gambar di atas. Ketika bilah berputar, udara di depan bilah akan menumbuk bagian bawah bilah. Karena hal ini, bilah akan mendapatkan gaya dorong ke atas. Besarnya gaya angkat (gaya dorong ke atas) ditentukan oleh kecepatan putar baling-baling, luas penampang bilah dan sudut serangan (angle of attact).
Agar helikopter bisa terbang ke depan, bidang putaran baling-baling bisa diubah miring ke depan sehingg gaya angkat tadi tidak vertikal tapi condong ke arah depan.

(Di bagian kokpit ada kontroler untuk mengatur kemiringan bidang putaran baling-baling).
Ketika baling-baling berputar, berlaku hukum kekekalan momentum sudut yang menyebabkan badan pesawat akan berputar berlawanan arah dengan arah putar baling-baling. Untuk mencegah berputarnya badan pesawat diperlukan gaya pembalik, yaitu dibuatnya baling-baling pada ekor pesawat.
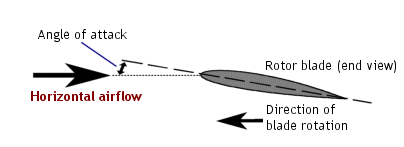
Ketika dilihat dari samping, bentuk bilah baling-baling helikopter akan tampak seperti gambar di atas. Ketika bilah berputar, udara di depan bilah akan menumbuk bagian bawah bilah. Karena hal ini, bilah akan mendapatkan gaya dorong ke atas. Besarnya gaya angkat (gaya dorong ke atas) ditentukan oleh kecepatan putar baling-baling, luas penampang bilah dan sudut serangan (angle of attact).
Agar helikopter bisa terbang ke depan, bidang putaran baling-baling bisa diubah miring ke depan sehingg gaya angkat tadi tidak vertikal tapi condong ke arah depan.

(Di bagian kokpit ada kontroler untuk mengatur kemiringan bidang putaran baling-baling).
Ketika baling-baling berputar, berlaku hukum kekekalan momentum sudut yang menyebabkan badan pesawat akan berputar berlawanan arah dengan arah putar baling-baling. Untuk mencegah berputarnya badan pesawat diperlukan gaya pembalik, yaitu dibuatnya baling-baling pada ekor pesawat.
Prinsip Kerja Baling-Baling Helikopter
Helikopter adalah sebuah pesawat yang mengangkat dan terdorong oleh satu atau lebih rotor (propeller) horizontal besar. Helikopter diklasifikasikan sebagai pesawat sayap-berputar untuk membedakannya dari pesawat sayap-tetap biasa lainnya. Kata helikopter berasal dari bahasa Yunani helix (spiral) dan pteron (sayap). Helikopter yang dijalankan oleh mesin diciptakan oleh penemu Slovakia Jan Bahyl.
Dibandingkan dengan pesawat sayap-tetap lainnya, helikopter lebih kompleks dan lebih mahal untuk dibeli dan dioperasikan, lumayan lambat, memiliki jarak jelajah dekat dan muatan yang terbatas. Sedangkan keuntungannya adalah gerakannya; helikopter mampu terbang di tempat, mundur, dan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Terbatas dalam fasilitas penambahan bahan bakar dan beban/ketinggian, helikopter dapat terbang ke lokasi mana pun, dan darat di mana pun dengan lapangan sebesar rotor dan setengah diameter. Landasan helikopter disebut helipad.
Prinsip kerja Helikopter
Helikopter bisa terbang karena gaya angkat yang dihasilkan oleh aliran udara yang dihasilkan dari bilah-bilah baling-baling rotornya. Baling-baling itu yang mengalirkan aliran udara dari atas ke bawah. Aliran udara tersebut sedemikian deras sehingga mampu mengangkat benda seberat belasan ton. Teorinya sebenarnya cukup sederhana namun prakteknya rumit.
[sunting]Airfoil
Pada dasarnya, prinsip dasar terbang dari pesawat bersayap tetap (fixed wing) dengan helikopter yang dikenal juga pesawat bersayap putar pada dasarnya tetap. Kuncinya ada pada dua kekuatan besar yang bekerja terpadu, menghasilkan gaya angkat dan daya dorong yang besar.
Pada pesawat bersayap tetap Kekuatan pertama dihasilkan oleh aliran udara di permukaan sayapnya yang membentuk sudut datang tertentu dengan flap yakni sayap kecil di belakangsayap yang posisinya ditegakkan. Sehingga aliran udara mengalir deras ke belakang bisa diarahkan balik ke atas. Udara yang mengalir di permukaan sayap bagian bawah menekan permukaan sayap yang relatif datar itu ikut menekan ke atas menimbulkan gaya angkat dan menyebabkan pesawat terangkat ke atas. Paling kurang 15 persen dari seluruh gaya yang dihasilkan, dipergunakan untuk mengangkat badan pesawat ke atas.
Kekuatan besar lainnya adalah gaya dorong yang dihasilkan aliran udara yang ada di permukaan sayap bagian atas yang bentuknya relatif lengkung. Ketika aliran udara yang dihasilkan oleh mesin mengalir ke belakang dan melalui sayap utama maka aliran udara itu terpecah. Aliran udara yang mengalir di atas permukaan sayap bagian atas lebih deras dari aliran udara yang menerpa di permukaan sayap bagian bawah. Tetapi tekanan udara yang mengalir deras di atas permukaan sayap atas, relatif lebih kecil dibanding dengan tekanan udara di permukaan sayap bagian bawah yang justru alirannya kurang deras. Perbedaan tekanan udara ini yang menyebabkan sayap pesawat terangkat ke atas. Untuk membayangkan seberapa besar gaya angkat itu, secara teori menyebutkan bahwa perbedaan tekanan udara sebesar 2.5 ounce per inci persegi dapat menghasilkan gaya angkat 20 pound per kaki persegi ( 1 kaki = 20 cm). Bisa dihitung, kalau luas sayap pesawat 1000 kaki persegi maka gaya angkat yang dihasilkan akan mencapai 10 ton.
Pada helikopter, fungsi sayap digantikan oleh baling-baling yang setiap baling-balingnya meski berukuran lebih kecil dari sayap pesawat biasa, namun ketika diputar, curvanya relatif sama dengan sayap pesawat. Untuk mendapatkan gaya angkat, baling-baling rotor harus diarahkan pada posisi tertentu sehingga dapat membentuk sudut datang yang besar. Prinsipnya sama dengan pesawat bersayap tetap, pada helikopter ada dua gaya besar yang saling memberi pengaruh. Aliran udara yang bergerak ke depan baling-baling menekan baling-baling sehingga bilah baling-baling terdorong balik ke belakang menghasilkan suatu gaya angkat kecil. Tetapi ketika ketika aliran udara bergerak cepat melewati bagian atas dan bawah bilah-bilah baling-baling, tekanan udara yang besar di antara baling-baling otomatis akan mengembang ke seluruh permukaan yang bertekanan lebih rendah, menyebabkan baling-baling terdorong ke atas dan helikopter pun terangkat. Yang perlu diingat, meski bilah-bilah baling-baling itu hanya beberapa lembar, namun dalam keadaan berputar cepat, ia akan membentuk suatu permukaan yang rata dan udara yang menekannya ke atas menimbukan tekanan besar yang akhirnya menghasilkan gaya angkat yang besar pula. Prinsip ini sama dengan fungsi propeler pada pesawat bermesin turboprop dan sama pula dengan "kitiran" mainan anak-anak itu.
Beberapa helikopter yang digunakan dalam perang, seperti Mi-26 Hind misalnya dilengkapi dengan sayap kecil yang disebut canard, fungsi pertamanya untuk meringankan beban rotor utama dan yang kedua untuk meningkatkan laju kecepatan dan memperpanjang jangkauan jelajah. Fungsi lain adalah sebagai gantungan senjata, rudal dan lain-lainnya. Dengan menambahkan sayap pendek ini, maka perbedaan fungsional antara pesawat tetap dengan helikopter menjadi samar. Pesawat bersayap tetap juga ada yang mampu terbang-mendarat secara vertikal (Vertical Take-off Landing/VTOL). Contonya, Harrier dari jenis Sea Harrier atau AV-8 Harrier.
Kelebihan pesawat bersayap tetap, terutama soal terbangnya karena pesawat berjenis ini memiliki platform yang lebar sehingga relatif lebih stabil saat melakukan penerbangan. Soal menerbangkannya, itu persoalan mengatur kemudi guling pada sayap dan stabilizer tegak dan datar yang ada pada ekornya. Tetapi pada Helikopter tidaklah demikian. Ketika bilah-bilah baling-baling rotornya menghasilkan gaya angkat rotornya sendiri sendiri bekerja memindahkan udara di atasnya ke bawah sebanyak banyaknya. Disaat itu berat udara yang dipindahkan mengurangi berat helikopter sehingga helikopter itu terangkat. Dan bila helikopter itu terangkat, berarti terjadi keseimbangan berat antara udara yang dipindahkan dari atas ke bawah dengan bobot helikopternya. Untuk mengoperasikan helikopter itu ada alat kemudi yang biasa disebutcollective pitch dan cyclic pitch masing-masing berfungsi sebagai pengatur gaya angkat dan pendorong helikopter untuk melaju ke depan. Begitu sederhana cara kerjanya, tetapi mentransformasikannya dalam sebuah teknologi sungguh pekerjaan yang sangat rumit.
[sunting]Tail rotor
Begitu pula halnya dengan konfigurasi rotor, bukan hanya sekedar bisa berputar lalu terbang dan mengambang. Sebab setap baling-baling diputar akan selalu menimbulkan tenaga putaran yang disebut dengan istilah umum torque. Untuk menghilangkan atau menangkal tenaga putar yang bisa menyebabkan badan helikopter itu berputar, maka perlu dipasang antitorque.
Antitorque ini dapat berupa tail rotor atau rotor ekor yang dipasang pada ekor pesawat yang juga berfungsi sebagai rudder. Konfigurasi ini dapat dilihat pada helikopter umumnya sepertiBell-412, Bell-205 atau UH-1 Huey, atau NBO-105, dan AS-330 Puma atau AS-335 Super Puma, AH-64 APACHE atau Mi-24 HIND. Selin menggunakan tail rotor, masih ada beberapa desai yang lain. Misalnya yang menggunakan sistem tandem seperti yang digunakan pada helikopter Boeing CH-47 Chinook atau CH-46 Sea Knight. Kedua rotor tersebut yang bersama-sama berukuran besar masing-masing ditempatkan di depan dan di belakang badan helikopter. Keduanya simetris namun memiliki putaran yang berlawanan arah . Maksudnya untuk saling meniadakan efek putaran yang ditimbulkan satu sama lain, intermesh dalam bahasa populernya. Cara lain adalah dengan konfigurasi egg-beater. Konfigurasi rancang bangun seperti ini digunakan pada helikopter Ka-25 Kamov buatan Rusia atau Kaman HH-43 Husky. Kedua baling-baling yang sama besarnya itu diletakkan dalam satu poros, terpisah satu sama lain dimana yang satu diletakkan diatas rotor lainnya. Keduanya berputar berlawanan arah. Maksudnya untuk menghilangkan efek putaran atau torque.
Selain ketiga cara diatas, dibuat juga konfigurasi tanpa rotor ekor. Helikopter ini desebut NOTAR (No Tail Rotor) ini memiliki sistem yang sedikit berbeda dengan sistem yang ada dimana memanfaatkan semburan gas panas dari mesin utama yang disalurkan melalui tabung ekor. Contohnya adalah helikopter MD-902 Explorer.
[sunting]Rotor Aktif atau Tilt Rotor dan Sayap Aktif atau Tilt Wing
Tinggal landas dan mendarat ala helikopter tetapi berkarakter terbang macam pesawat bersayap tetap merupakan konsep yang dianut oleh helikopter jenis ini. Cara paling mudah adalah menggabungkan konsep kerja pesawat helikopter dengan pesawat bersayap tetap dalam satu wujud.
Prinsip kerjanya secara teknis bila rotor utama diarahkan ke atas maka gerakan vertikal yang dilakukan helikoter dapat dilakukan sedangkan saat rotor diarahkan ke depan atau ke belakang (sebagai pursher atau pendorong) maka karakter terbang seperti pesawat tetap dapat diperoleh. Gerakan rotor seperti ini tidak perlu melibatkan sayap.
Sebenarnya pengembangan rotor aktif ini masih diliputi kegamangan, masalahnya adalah sistem tadi bisa saja disebut pesawat bersayap tetap karena memiliki sayap yang berlumayan besar, sekaligus memiliki ekor pesawat yang berkonfigurasi dengan pesawat bersayap tetap biasa. Akhirnya konsep ini disebut dengan konsep hybrid. Contoh helikopter ini adalah V-22 Osprey. Selain konsep rotor aktif, ada pula konsep sayap aktif, dimana yang digerakkan bukanlah rotor seperti pada rotor aktif melainkan sayap pesawatnya. Sementara mesin tetap pada kedudukannya. Contoh helikopter ini adalah TW-68 yang dirancang oleh Ishida Corporation, Jepang, Rancangan ini disebut-sebut sebut sebagai memiliki rancangan yang lebih ringkas dibandingkan dengan rotor aktif hanya sayangnya keberlanjutannya tidak begitu terdengar.
[sunting]Kursi Lontar pada Helikopter
Dibandingkan pada pesawat biasa khususnya pesawat tempur, pesawat helikopter umumnya tidak dilengkapi dengan kursi lontar. Hal ini disebabkan karena masalah menghadapi rotor helikopter saat meluncurkan kursi lontar sekaligus umumnya helikopter terbang lebih rendah sehingga lebih rentan. Namun demikian pada helikopter Rusia, Kamov Ka-50 Hokum yang menggunakan kursi lontar yang dirancang khusus seperti Zvesda K-37-800. Langkah kerjanya adalah ketika kursi lontar diaktifkan, maka rotor diledakkan dan lepas dari kedudukannya, kemudian kedua sisi atas kaca kokpit membuka dan roket penarik aktif yang menarik pilot dan kirsinya keluar dari badan heli. Meski dirasa rumit, Helikopter masa depan akan dilengkapi dengan kursi lontar
[sunting]Penemuan Helikopter
Sebenarnya, perjalanan helikopter menjadi bentuk yang dikenal pada saat ini memakan kurun waktu yang cukup panjang. Dalam perjalanannya, juga melibatkan perkembangan teknologi dan juga para penemu serta pengembang helikoter.
Helikopter pertama yang menerbangkan manusia adalah Helikopter Breguet-Richet, tahun 1907. Heli ini terbang di Douai, Perancis pada 29 September 1907. Helikopter ini masih memperoleh bantuan dari empat orang yang memegangi keempat kakinya. Upaya ini tidak memperoleh catatan baik sebagai helikopter pertama yang terbang bebas. Walaupun demikian, helikopter ini membuktikan keberhasilan teori terbang vertikal yang saat itu masih dianggap sebagai teori. Ini merupakan mesin pertama yang bisa terbang dengan sendirinya membawa seorang pilot secara vertikal sebagai akibat daya angkat sayap putarnya. Heli ini menggunakan mesin Antoinette berkekuatan 50 hp.
Terbang heli sesungguhnya dilakukan oleh Paul Cornu menggunakan heli bermesin ganda Antoinette 24 hp di Lisieux, Perancis pada 13 November 1907. Penerbangan berlangsung 20 detik hingga ketinggian 0,3 Meter. Sedangkan Helikopter berjenis Gyroplane pertama diraih oleh C4 Autogiro buatan Juan de la Cierva. Autogiro terbang pertama pada 9 Januari 1923. Rahasia sukses pada pengadopsian sistem flapping hinges joint the blades to the rotor head. Sementara helikopter yang sukses terbang pertama dilakukan oleh jenis Fock Wulf FW-61berotor ganda yang didesain oleh Professor Heinrich Focke pada tahun 1933-1934. Helikopter ini melakukan terbang perdananya pada 26 Juni 1936 dan ditenagai oleh mesin Siemens-Halske Sh 14A bertenaga 160 hp. Heli ini diterbangkan oleh Ewald Rohlfs. Heli ini mencatat rekor terbang sejauh 122,35 km dan lama terbang satu jam 20 menit 49 detik. Pada waktu lain ia terbang hingga ketinggian 3427 meter dan rekor kecepatan 122 km/jam.
[sunting]Pionir pengembang teknologi Helikopter
[sunting]Leonardo da Vinci (1452-1519)
Leonardo da Vinci sebenarnya mengembangkan konsep terbang vertikal yang sebelumnya merupakan mainan anak-anak dari dataran Cina, tidak jelas sebenarnya sejak kapan mainan anak-anak ini dikembangkan disana dan siapa inisiatornya atau penemunya. Pada tahun 1483 Leonardo da Vinci mengembangkan konsep sekrup terbang.
[sunting]Sir Goerge Cayley (1773-1857)
Sir George Cayley dikenal sebagai insinyur dan inovator dalam navigasi udara dan aerodinamika. Salah satu yang dikenalkannya adalah istilah angle of attack dalam dunia penerbangan. Dalam sejarah, dia merupakan sosok yang mengembangkan pesawat sayap tetap dan pesawat layang atau glider namun demikian dia mengembangkan sayap putar atau helikopter. Helikopter yang diperkenalkannya merupakan kompilasi dari bahan kayu, bulu, gabus dan kawat.
Pada 1842, Cayley mendesain helikopter lebih baik , khususnya ketika mengetahui bahwa putaran baling-baling dapat menimbulkan petaka sehingga memerlukan penangkalnya. Teori penangkal ini juga dikemukakan olehnya. Agar bisa terbang, helikpter ini menempatkan dua rotor yang bergerak berlawanan arah. Meski helikopter rancangannya belum berwujud dengan helikopter yang mengudara, konsep helikopternya dipakai oleh Kamov dari Rusia dan Focke dari Jerman.
[sunting]Nikolai Egorovich Zhikovsky (1847-1921)
Zhukovsky mengawali karier di dunia penerbangan dengan menekuni matematika, hidrodinamika dan aerodinamika. Zhukovsky kemudian menemukan terowongan angin pertama di dunia untuk menguji teknologi aerodinamika. Terjun dalam pengembangan helikopter pada tahun 1910 dan pada Perang Dunia I mengembangkan banyak pesawat terbang dan helikopter
[sunting]Juan de la Cierva (1895-1936)
Cierva mengembangkan helikopter setelah pesawat pembom bersayap ganda buatannya jatuh pada tahun 1919, alasannya adalah kestabilan helikopter dianggapnya lebih tinggi. Dalam membangun rancangan helikopternya, Cierva mengabaikan berbagai teori yang berkembang sebelumnya, dengan menggunakan rancangan-rancangan baru buatannya yang didasarkan pada teori yang dikembangkannya lewat berbagai eksperimen. Hasinya adalah Autogiro yang merupakan konsep pesawat gado-gado antara pesawat terbang umumnya sehingga bisa melakukan terbang landas secara vertikal, yang setengah pesawat terbang dan setengah helikopter. Autogiro Cierva terbang pada 1923. Lima tahun kemudian Cierva melakukan penerbangan keliling Eropa dengan Autogiro sejauh lebih dari 5000 km seraya berpromosi. Upayanya tidak sia-sia karena Autogiro rancangannya banyak diminati sejumlah industri di Eropa. Cierva meninggal dalam kecelakaan Autogiro di Croydon pada tahun 1936.
[sunting]Igor Ivanovich Sikorsky (1889-1972)
Sikorsky menaruh minat pada penerbangan dengan merancang berbagai pesawat model di antaranya berupa helikopter sejak usia dini. Pada awalnya dia masuk Naval Academy di St. Petersburg yang kemudian mengundurkan diri dan pergi ke Paris untuk mendalami ilmu teknik dan penerbangan. Setelah dari Paris, dia kembali ke Kiev, Ukraina dan mengembangkan helikopter namun gagal. Revolusi Bolshevik memaksa Sikorsky hijrah ke Paris dan selanjutnya menetap di Amerika Serikat.
Pada tahun 1939 dia menerbangkan helikopter pertamanya VS-300 dan selama pengembangannya, helikopternya mencatat berbagai rekor penerbangan. Sampai memasuki abad ke-21 ada sekitar 40.000 helikopter buatan Sikorsky terbang diberbagai belahan dunia ini.
[sunting]Mikhail Mill (1909-1970)
Seperti halnya Sikorsy, Mill menaruh minat pada penerbangan diusia dini. Dia memenangkan kompetisi pesawat model pada usia 12 tahun. Ia kemudian masuk ke Insitut Aviasi di Novocherkassk dan mengembangkan autogiro pertamanya dengan pengawasan dan bimbingan Kamov dan Skrzhinsky. Setelah lulus pada 1931, dia masuk ke pusat aerodinamika Rusia TsAGi, dan disinilah melakukan penelitian pada aerodinamika helikopter dengan penekanan pada stabilitas dan desain rotor.
Pada tahun 1947, Mil diangkat menjadi kepala desain helikopter yang baru dan memunculkan helikopter GM-1 yang dikenal menjadi Mi-1 Hare. Sukses Hare menuntun pengembangan helikopter selanjutnya yang sangat terkenal seperti Mi-4, Mil Mi-6 Hook, Mi-8 dan lain-lain.
[sunting]Yum Soemarsono (1916-1999)
Yum Soemarsono dikenal sebagai bapak helikopter Indonesia. Berbeda dengan penemu dan pengembang helikopter lainnya, dia mengembangkan helikopter sendiri berdasarkan pengalaman dan intuisi serta keterampilannya yang tidak diperoleh dari pendidikan tinggi. Rancangannya berupa Rotor Stabilizer dibuatnya hanya berdasarkan intuisi.
Helikopter pertama rancangannya adalah RI-H yang selesai pada tahun 1948 namun tidak sempat diterbangkannya karena lokasi pembuatannya di Gunung Lawu dibom Belanda pada saat Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Heli kedua adalah YSH yang dirancang bersama Soeharto dan Hatmidji, selesai pada tahun 1950 dan melayang setinggi 10 cm di lapangan SekipYogyakarta. Sementara Helikopter ketiga adalah Seomarcopter yang berhasil terbang ketinggian 3 meter sejauh 50 meter dengan mesin berdaya 60 hp pada 1954. Helikopter ke empat adalah Kepik yang ironisnya mengalami kecelakaan dan menyebabkan kehilangan tangan kirinya dan sekaligus menewaskan asistennya, Dali. Nama kepik sendiri adalah nama pemberian presiden Republik Indonesia pertama Soekarno.
Kehilangan tangan kirinya membuatnya menemukan suatu alat yang dinamakan throttle collective device untuk mengganti tangan kirinya yang putus, sehingga penerbang cacat masih mampu menerbangkan helikopter. Alat ini digunakan untuk mengangkat dan memutar collective, salah satu kemudi yang terletak pada sisi kiri penerbang. Semula hanya didesain untuk helikopter jenis Hiller, namun kemudian dikembangkannya untuk dipakai pada helikopter Bell 47G dan Bell 47J2A, hadiah dari Solichin GP. Meski alat ini kemudian diminati oleh pabrik helikopter Bell di Amerika Serikat, tidak ada kejelasan selanjutnya mengenai pengembangan alat ini dan sekaligus juga hak patennya. Beliau meninggal pada 5 Maret 1999.
Kamis, 14 Juli 2011
Tesis PKLH
BAB I
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian
Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat potensial berupa sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang tinggi keanekaragamannya dengan keunikan, keaslian dan keindahan. Kekayaan tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian antara aspek perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.
Manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, semua kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, dengan tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Penetapan suatu kawasan baik di daratan dan atau perairan sebagai kawasan konservasi. Kawasan pelindung alam (KPA) yang merupakan perwakilan dari keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, keutuhan sumber plasma nutfah, keseimbangan ekosistem, serta keunikan dan keindahan alam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup untuk masa kini maupun masa yang akan datang serta menunjang kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat sekitar kawasan konservasi, merupakan masyarakat yang mendambakan suatu perubahan sosial dari kondisi kehidupannya. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan ilmiah, teknik dan metoda. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan kemandirian masyarakat daerah penyangga kawasan konservasi. Kawasan pelindung alam (KPA) adalah upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mereka mampu mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kebutuhan obyektif masyarakat itu sendiri dalam suatu ekosistem hutan yang lestari.
Pengelolaan kawasan konservasi tidak akan terlepas dari masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu masyarakat sangat penting untuk dilibatkan di dalam suatu sistem pengelolaan kawasan konservasi. Pembangunan kawasan konservasi diarahkan kepada pemanfaatan multi fungsi, dengan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan ekologi, serta dengan melibatkan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.
Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi merupakan keharusan yang menjadi tanggung jawab pengelola hutan itu sendiri yaitu perum perhutani, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, untuk mencapai kondisi yang diharapkan yaitu peningkatan status sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian kawasan konservasi itu sendiri.
Perubahan paradigma pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan tersebut, diimplementasikan oleh Perum Perhutani dalam sistem Pengeolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Seluruh jajaran Perum Perhutani bergerak bersama secara terus menerus mensosialisasikan kegiatan PHBM tersebut keseluruh lapisan masyarakat desa hutan yang ada di pulau jawa, termasuk ke Masyarakat Desa Hutan yang ada di Desa wana suka mekar
PHBM merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan secara bersama-sama antara perhutani dengan masyarakat desa hutan atau perhutani dengan dan masyarakat desa hutan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Dalam program PHBM ini masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap kegiatan program, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan tujuan dari kegiatan PHBM, yaitu untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Masyarakat yang ikut kegiatan PHBM di Desa Suka Mekar tiap tahun terus meningkat.
Tabel. 1 Masyarakat Desa Suka Mekar yang ikut kegiatan PHBM
| No | Tahun | Jumlah |
| 1 | 2007 | 74 orang |
| 2 | 2008 | 99 orang |
| 3 | 2009 | 150 orang |
| 4 | 2010 | 210 orang |
Sumber : Buku anggota LMDH Wana Suka Mekar tahun 2007-2011
: Data kegiatan LMDH Bidang HHBK HPD
Kegiatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan Perum Perhutani bersama-sama dengan masyarakat, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat PHBM. Keberhasilan program PHBM di LMDH Wana Suka Mekar dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatnya pendapatan. Berikut merupakan tabel rata-rata pendapatan anggota.
Tabel. 2. Pendapatan masyarakat angota LMDH Wana Suka Mekar dengan adanya Program PHBM
| NO | Tahun | Pendapatan |
| 1 | 2008 | 500.000,00 – 700.000,00 |
| 2 | 2009 | 1000.000,00 – 1200.000,00 |
| 3 | 2010 | 1700.000,00 – 2000.000,00 |
Sumber : Laporan Pendapatan Anggota LMDH Wana Suka Mekar
Berdasarkan tabel tersebut adanya program PHBM ini dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat, khususnya petani peserta program PHBM pedapatan masyarakat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami peningkatan.
Keberhasilan Program PHBM di LMDH Wana Suka Mekar juga memberikan implementasi terhadap keberhasilan tanaman. Berikut merupakan tabel dampak implementasi PHBM dalam pengaruhnya terhadap keberhasilan tanaman.
Tabel. 3 Implementasi kegiatan PHBM terhadap keberhasilan tanaman
| NO | Tahun | Keberhasilan Tanaman ( % ) |
| 1. | 2002 | 82,80 |
| 2. | 2003 | 84,80 |
| 3. | 2004 | 84,95 |
| 4. | 2005 | 94,71 |
| 5. | 2006 | 97,75 |
| 6. | 2007 | 97,87 |
| 7. | 2008 | 95,30 |
| 8. | 2009 | 99,09 |
| 9 | 2010 | 99,30 |
Sumber : BKPH Sukanagara Utara
Berdasarkan tabel dampak implementasi PHBM diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan tanaman dari tahun 2002 sampai 2010 terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini berarti PHBM sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan tanaman. Peningkatan tersebut merupakan bukti adanya peningkatan keamanan terhadap pengelolaan tanaman antara masyarakat dan pihak perum perhutani yang berjalan efektif dan efisien.
Keberhasilan PHBM tersebut dengan diberikannya Piagam penghargaan oleh Menteri kehutanan kepada ketua LMDH Wana Suka Mekar yang meraih juara Terbaik II kategori LMDH Perum Perhutani dalam bidang Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2010 LMDH yang berdiri tahun 2005 berakte notaris No 11 tanggal 11 Mei 2007 mengelola HPD seluas 1.071,8 hektar dan memiliki anggota sebanyak 633 orang wilayah kerja RPH Campaka, BKPH Sukanagara Utara, KPH Cianjur, masuk dalam wilayah admnistrasi pemerintahan Kp Ciharum, Ds Sukamekar, Kec Sukanegara, Kab Cianjur.
Atas penghargaan piagam tersebut partisipasi masyarakat LMDH Wana Suka Mekar menjadi lebih aktif dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Selain itu dengan penghargaan piagam tersebut diharapkan masyarakat dapat menumbuhkan rasa memiliki dan turut bertanggung jawab masyarakat terhadap terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya hutan. Hal ini berakibat keberadaan hutan dan keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan dapat terjaga.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan konteks di atas maka fokus penelitian ini adalah : Bagaimana partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan melalui kegiatan PHBM di perum perhutani RPH Campaka kabupaten cianjur. Agar kajian menjadi lebih tajam dan mendalam maka fokus penelitian dibagi menjadi sub-sub fokus sebagai berikut:
1. Bagaimana upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam meningkatkan partisispasi masyarakat dalam pengembangan agroforestri?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam memberdayakan masyarakat?
3. Bagaimana pembinaan yang dilakukan Perum Perhutani dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di LMDH Wana Suka Mekar RPH Campaka kabupaten cianjur?
4. Upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam mengatasi kendala dan hambatan dalam kegiatan PHBM?
C. Manfaat Penelitian
1. Memberikan informasi kepada Perum Perhutani tentang Bagaimana partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan melalui kegiatan PHBM di Perum Perhutani RPH Campaka Kabupaten Cianjur.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi peneliti berikutnya.
BAB II
ACUAN TEORITIK
A. Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi merupakan bentuk kegiatan ikut serta menyumbangkan sesuatu yang dimilki sebagai respon terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Sebenarnya Definisi partisipasi sangat beragam. Partisipasi menurut Hendar dan Kusnadi. Partisipasi adalah peran serta (keikutsertaan) seseorang atau sekelompok orang dalam aktivitas tertentu.[1]
Partisipasi menurut Katz dalam Hessel Nogi S, adalah keterlibatan dan komitmen sejumlah individu atau kelompok dalam perumusan dan keputusan pembangunan.[2]
Partisipasi menurut Keith Davis dalam Hessel Nogi S, sebagai berikut:
”Participation is defined as an indidual as mental and emotional involvement in a group situation that encourages him to cotribute to group goals and to share responsibility for them.[3]
Partisipasi menurut Soeharjo dalam Hessel Nogi S, Partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri (self-reliance) dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat.[4]
Berdasarkan kajian teori-teori tersebut partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (Individu) atau kelompok dalam merumuskan dan memberi keputusan. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Partisipasi diartikan sebagi keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.
Partisipasi menurut Cees Leeuwis, merupakan proses dimana pemangku kepentingan mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif pembangunan dan keputusan serta sumber daya yang mempengaruhi.[5]
Partisipasi menurut Adinugroho, W. C. , I N.N. Suryadiputra, merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk bersedia memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan kelompok dan turut bertanggungjawab atas usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya.[6]
Partisipasi masyarakat menurut Petrus Citra, adalah keterlibatan seseorang dalam memberi sumbangan/mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Dengan sendirinya diharapkan bahwa partisipasi tersebut dapat bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran penuh.[7]
Partisipasi menurut Sri Murtono, bukan hanya keterlibatan secara fisik, melainkan lebih jauh adalah bagaimana peran serta dalam kegiatan dan tanggung jawab setelah kegiatan tersebut berhasil.[8]
Berdasarkan kajian teori-teori tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.
Berdasarkan kajian teori-teori yang dikemukakan di atas maka dapat disintesiskan, bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan aktif dan sadar seseorang atau kelompok untuk turut serta mengambil keputusan dan pelaksanaan suatu kegiatan hingga merasakan hasilnya melalui penilaian yang dilakukan dan sekaligus siap memikul beban dan bertanggungjawab atas keputusan yang diambil baik secara mental maupun fisik.
2. Pelestarian Hutan
Menurut Arifin Arief, Pelestarian hutan adalah bentuk dan proses pengelolaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga secara terus-menerus dapat memberikan produksi dan jasa yang diharapkan, tetapi tetap tidak mengurangi fungsi hutan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan.[9]
Menurut Arifin Arief, Melestarikan hutan adalah pemanfaatan hutan secara lestari dan pengawetan berbagai sumber alam yang berada di dalam maupun di sekitar hutan.[10]
Menurut Frans Wanggai, Pelestarian hutan adalah perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfatan secara lestari sumberdya alam hayati dan ekosistem.[11]
Berdasarkan teori tersebut pelestarian hutan adalah menyelamatkan semua komponen kehidupan, hutan yang terjaga agar hutan tetap mampu menjalankan fungsi dan manfaatnya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang
Kusumaatmaja dalam LIPPI, mengemukakan bahwa kita perlu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam hayati maupun non hayati, karena pada umumnya sumberdaya alam tersebut merupakan daerah resapan air yang harus kita jaga, pertahankan, dan lestarikan.[12]
Alfian dalam LIPPI, mengemukakan bahwa faktor latar belakang budaya seseorang atau kelompok juga berperan dan ikut serta dalam melestarikan dan menyeimbangkan lingkungan.[13]
Berdasarkan teori tersebut menjaga kelestarian hutan sangatlah penting karena dengan dijaganya kelestarian hutan akan berdampak positif pada kelangsungan hidup lainnya diantaranya persediaan air dan banjir, serta longsor dapat diantisipasi. Partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan merupakan kunci penting dalam menghindari timbulnya kerusakan hutan. adanya kegiatan PHBM kelompok masyarakat petani LMDH yang tinggal di sekitar hutan milik perum perhutani ikut berpartisipasi dalam melestarikan hutan salah satunya melalui kegiatan program PHBM dengan kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan, menjaga kawasan hutan, Motivasi dan tanggungjawab bersama dalam pengelolaan hutan, perlindungan dan konservasi alam yang meliputi berbagai ilmu mendukung dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan perum perhutani.terlibat langsung dalam melestarikan hutan. yang bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) khususnya pihak di luar dari perum perhutani yang mempunyai perhatian yang sangat besar dan berperan mendorong optimalisasi serta berkembangnya pengelolaan dan pelestarian hutan yang dilakukan bersama masyarakat.
Berdasarkan teori tersebut dapat disintesiskan partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan ini adalah sebagai proses untuk berbagi peran, berbagi ruang dan waktu, Dengan melibatkan masyarakat desa hutan dalam setiap tahapan pelestarian hutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi akan memberi makna yang dalam bagi mereka. Motivasi dan tanggung jawab bersama dalam pelestarian hutan akan muncul dari proses-proses yang dilalui dalam peranserta masyarakat dalam melestarikan hutan
B. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat menurut Zimmerman dalam Randy R. Wrihantolo. pemberdayaan adalah tindakan kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat dan hubungan antara organisasi masyarakat.[14]
Pemberdayaan masyarakat menurut Cornel EG, dalam Randy R. Wrihantolo. Pemberdayaan sebagai suatu proses sengaja yang berkelanjutan, berpusat pada masyarakat lokal, dan melibatkan prinsip saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian, dan partisipasi kelompok, dan melalui proses tersebut orang-orang yang kurang memiliki bagian yang setara akan sumber daya berharga meperoleh akses yang lebih besar dan memiliki kendali atas sumberdaya tersebut.[15]
Pemberdayaan masyarakat menurut Lyons, et al, dalam Randy R. Wrihantolo. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dilalui agar masyarakat memperoleh kendali lebih besar akan urusan/masalah mereka dan meningkatkan inisiatif yang berhubungan dengan nasib mereka sendiri.[16]
Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikanperanan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.
Menurut Rafiq A, pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Proses tersebut dilakukan dengan memfasilitasi masyarakat agar mampu (a).menganalisis situasi kehidupan dan segala permasalahan yang dihadapi (b).mencari pemecahan permasalahan berdasarkan kemempuan dan keterbatasan yang dimiliki (c).mengembangkan usaha dengan segala kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki (d).mengembangkan sistem untuk mengakses sumberdaya yang diperlukan.[17]
J. Kaloh, mengemukakan pemberdayaan bukan berarti menjadikan masyarakat selalu tergantung kepada pihak lain. lebih ditujukan untuk memandirikan masyarakat dalam mengurus kepentingannya melalui Proses pembangunan partisipatif dengan pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemerintah, dalam pengertian perorangan (aparat) maupun institusi (instansi) harus dapat memahami bahwa perannnya sangat penting dan signifikan dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat.[18]
Berdasarkan teori tersebut pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Berdasarkan teori tersebut dapat disintesiskan pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Disini subyek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat.
C. Pengembangan Agroforestri
1. Konteks Agroforestri
Agroforestri menurut Dadan mulyana & Ceng asmarahman agroforestri merupakan suatu pola penggunaan lahan yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan hasil dengan efektif, caranya, menanam suatu lahan dengan menggabungkan atara tumbuhan berkayu (tanaman hutan) dengan tanaman pangan atau pakan ternak degan menggunakan praktik-praktik pengolahan yang sesuai dengan kondisi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya setempat.[19] Agroforestri menurut Karwan A. Salikin. Merupakan pola tanam tumpangsari antara tanaman tahunan, khususnya tanaman hutan, dan tanaman semusim, misalnya tanaman obat-obatan. Tanaman tahunan mampu menyimpan banyak air dan menghasilkan humus dari serasah dedaunan, serta memberikan naungan bagi tanaman semusim. Sebaliknya, tanaman semusim mampu menahan laju erosi permukaan tanah.[20] Agroforestri menurut H De Foresta, A Kusworo Dkk. Agroforestri adalah hutan buatan yang didominasi tanaman serbaguna yang dibangun petani pada lahan-lahan pertanian. Dilihat dari jauh agroforestri tampak lebih teratur ketimbang hutan alam primer. Diamati dari dekat berisi campuran pepohonan, rerumputan, dan aneka tumbuhan lain: mulai dari lumut, pakis-pakisan, semak, pakis besar, tumbuhan merambat, dan anggrek.[21]
Berdasarkan teori tersebut agroforestri dapat dikatakan suatu sistem yang mengkombinasikan antara komponen hutan dengan komponen pertanian. Sehingga akan dihasilkan suatu bentuk pelestarian alam yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi pelakunya serta juga dapat digunakan untuk pelestarian alam. Agroforestri merupakan ilmu baru dengan teknik lama, maksudnya bahwa sebenarnya agroforestry sudah diaplikasikan oleh masyarakat pada jaman dahulu dan sekarang tehnik ini digunakan kembali, karena dirasa sangat bermanfaat bagi alam dan masyarakat sekarang. Pengembangan agroforestri menurut Raintree dalam Widianto, Nurheni Wijayanto Dkk. meliputi tiga aspek, yaitu (a) meningkatkan produktifitas sistem agroforestri, (b) mengusahakan keberlanjutan sistem agroforestri yang sudah ada dan (c) penyebarluasan sistem agroforestri sebagai alternatif atau pilihan dalam penggunaan lahan yang memberikan tawaran lebih baik dalam berbagai aspek (adoptability)[22] Agroforestri dikembangkan untuk memberi manfaat kepada manusia atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produktifitas sistem agroforestri diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah pengembangan pedesaan dan seringkali sifatnya mendesak. Agroforestri utamanya diharapkan dapat membantu mengoptimalkan hasil suatu bentuk penggunaan lahan secara berkelanjutan guna menjamin dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat dalam bidang (ekonomi). Sistem berkelanjutan ini dicirikan antara lain oleh tidak adanya penurunan produksi tanaman dari waktu ke waktu dan tidak adanya pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut merupakan refleksi dari adanya konservasi sumber daya alam yang optimal oleh sistem penggunaan lahan yang diadopsi. Dalam mewujudkan sasaran ini, agroforestry diharapkan lebih banyak memanfaatkan tenaga ataupun sumber daya sendiri (internal) dibandingkan sumber-sumber dari luar. Di samping itu agroforestri diharapkan dapat meningkatkan daya dukung ekologi manusia, khususnya di daerah pedesaan. Untuk daerah tropis, beberapa masalah (ekonomi dan ekologi) berikut menjadi mandat agroforestri dalam pemecahannya. Berdasarkan paparan di atas maka dapat di sintesiskan bahwa Agroforestri merupakan suatu sistem dengan menggabungkan beberapa komponen hutan dengan komponen pertanian atau ternak (hewan), sehingga sistem ini dapat berperan untuk memperbaiki kondisi lingkungan secara global maupun spesifik serta dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku/petani agroforestri.
a. Pola tanam Pola Tanam dalam agroforestri sangat spesifik karena menyangkut berbagai komponen yang berbeda didalamnya. Prinsip pola tanam dalam agroforestri adalah bagaimana memanfaatkan ruang dan waktu secara optimal sehingga unsur-unsur hara, air dan cahaya dapat dimanfaatkan secara optimal pula. Dalam usaha memanfaatkan ruang secara optimal ditempuh berbagai cara, diantaranya pengaturan jarak tanam, tata-letak tanaman, perkembangan lapisan tajuk dan perakaran. Optimalisasi pemanfaatan unsur waktu dilakukanantara lain dengan pengaturan waktu tanam dan panen. Dengan pengaturan ruang dan waktu yang optimal diharapkan komponen yang satu tidak akan menekan komponen yang lain, malah sebaliknya terjadi saling menunjang antar komponen. Menurut Nair dalam Mohamad Soerjani, Agroforestri adalah suatu nama kolektif untuk sistem-sistem penggunaan lahan teknologi, dimana tanaman keras berkayu (pohon-pohonan, perdu, jenis-jenis palm, bambu, dsb) ditanam bersamaan dengan tanaman pertaian, dan/atau hewan, dengan suatu tujuan tertentu dalam suatu bentuk pengaturan spasial atau urutan temporal, dan didalamnya terdapat interaksi-interaksi ekologi dan ekonomi diantara berbagai komponen yang bersangkutan.[23] Berdasarkan teori tersebut Pola tanam dalam agroforestri diatur sedemikian rupa sehingga pada tahap awal, dimana faktor naungan belum menjadi masalah, beberapa komponen dapat tumbuh bersamaan dalam satu bentuk pengaturan spasial lapisan tajuk. Pada tahap lanjut agroforestri akan menyerupai ekosistem hutan yang terdiri dari banyak lapisan tajuk (multi strata). Lapisan tajuk atas ditempati oleh jenis-jenis dominan, dibawahnya ditempati oleh jenis-jenis yang kurang dominan yang tahan setengah naungan, kemudian lapisan bawah ditempati oleh jenis-jenis tahan naungan.
b. Produktivitas Widianto, Nurheni Wijayanto Dkk, mengemukakan produk yang dihasilkan sistem agroforestri dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni (a) yang langsung menambah penghasilan petani, misalnya makanan, pakan ternak, bahan bakar, serat, aneka produk industri, dan (b) yang tidak langsung memberikan jasa lingkungan bagi masyarakat luas, misalnya konservasi tanah dan air, memelihara kesuburan tanah, pemeliharaan iklim mikro, pagar hidup, dsb.[24] Peningkatan produktivitas sistem agroforestri diharapkan bisa berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat desa penyempurnaan seluruh kegiatan produktivitas yang agroforestri ini harus memegang peranan utama di dalam perencanaan dan usaha pengelolaan hutan. Pendekatan seutuhnya seperti ini dapat memberikan perlindungan terhadap hutan, menambah pendapatan penduduk, dan meningkatkan produksi nasional secara terpadu dan lebih efektif. Peningkatan produktivitas sistem agroforestri dilakukan dengan menerapkan perbaikan cara-cara pengelolaan sehingga hasilnya bisa melebihi yang diperoleh dari praktek sebelumnya, termasuk jasa lingkungan yang dapat dirasakan dalam jangka panjang. Namun demikian, keuntungan (ekonomi) yang diperoleh dari peningkatan hasil dalam jangka pendek seringkali menjadi faktor yang menentukan apakah petani mau menerima dan mengadopsi cara-cara pengelolaan yang baru. Perbaikan (peningkatan) produktivitas sistem agroforestri dapat dilakukan melalui peningkatan dan/atau diversifikasi hasil dari komponen yang bermanfaat, dan menurunkan jumlah masukan atau biaya produksi.
D. Pembinaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto dalam Y Harsono adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apa saja yang dapat dikuasainya dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya.[25]
Ekonomi kerakyatan menurut Gunawan Sumodiningrat dan Riant Nugroho adalah sistem ekonomi yang mempunyai misi pemberdayaan rakyat dengan sifat menjaga dan mengembangkan yang sudah kuat, pemberdayaan yang lemah, dan membangun kemitraan profesional yang dilandasi semangat kooperasi di antara para pelakunya maupun dengan pelaku global.[26]
Ekonomi kerakyatan menurut Sarbini Sumawinata adalah suatu strategi pembangunan yang lain dari strategi pembangunan yang sampai sekarang diadakan, yaitu seluruh kemampuan investasi yang tersedia sebagai dana pembangunan nasional nasional untuk bagian yang cukup besar.[27]
Ekonomi kerakyatan menurut Muslimin Nasution, Ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan masyarakat maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatiakan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan.[28]
Ekonomi kerakyatan menurut Hasanudin Rahman dan Naja, Ekonomi Kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian dimana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekonomi itu pun berada dibawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.[29]
Berdasarkan teori-teori tersebut ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang benar-benar berorientasi pada kekuatan dan sekaligus kepentingan rakyat banyak. Ekonomi kerakyatan ini adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam ekonomi kerakyatan yang demokratis ada pemihakan sepenuh hati dari pemerintah kepada mereka yang lemah dan miskin pada sektor ekonomi rakyat
Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah masyarakat secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sistem antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.
Pengembangan ekonomi kerakyatan menurut Muslimin Nasution, Ekonomi kerakyatan dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan yang berkeadilan dan keadilan yang berperikemanusiaan sebagai cara dan mekanisme dasar dalam mewujudkan tujuan ekonomi nasional. Untuk ini, sistem nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila serta mekanisme pencapaian tujuannya yang jelas, transparan, dan berkeadilan bagi penyelenggaraan Negara, pelaku ekonomi dan masyarakat merupakan dasar bagi penyelenggaraan ekonomi nasional.[30]
Ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. akhirnya dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Dari pernyataan tersebut dapat di sintesiskan, Bahwa ekonomi kerakyatan dikembangkan Oleh Perum Perhutani melalui Kegiatan PHBM dengan pola agroforestri dilakukan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan kehidupan masyarakat. PHBM pola agroforestri sebagai sumber ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
E. Kendala dan Hambatan Dalam Kegiatan PHBM Menurut Yuliana Cahya Wulan, Yurdi Yasmi Dkk. kendala dan hambatan PHBM di perum perhutani belum menjawab masalah yang ada di masyarakat yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan subsistem kayu, bagaimana memperluas ruang kelola masyarakat, dan bagaimana mencipatakan hubungan yang harmonis antara perum perhutani dan masyarakat masyarakat juga menilai bahwa PHBM belum sepeuhnya sesuai dengan konsep awalnya. Sebagai contoh dalam pembagian hasil, maka proporsi yang diterima masyarakat 25 persen dan untuk perum perhutani 75 persen. Namun apabila produksi berkurang karena adanya kerusakan, maka yang dikurangi adalah proporsi hak masyarakat, sedangkan hak Perum Perhutani tetap, selain itu, masyarakat juga merasa jarang dilibatkan pada pertemuan-pertemuan dalam pengambilan keputusan.[31] Ani Adiwinata Nawir, Murniati Dkk kendala dan hambatan PHBM di perum perhutani Kegiatan yang bersifat ke proyekan menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemeliharaan pohon yang sudah ditanam, tidak adanya strategi pemasaran jangka panjang atau tujuan ekonomi lainnya dalam perencanaan proyek, kurang dipertimbangkannya aspek sosial budaya, tidak efektifnya usaha pengembangan kapasitas masyarakat, terbatasnya partisipasi masyarakat karena masalah kepemilikan lahan yang belum terselesaikan dan tidak efektifnya organisasi masyarakat, Pada skala yang lebih luas, kurang jelasnya pembagian hak dan kewajiban antar pemangku kepentingan, khususnya pemerintah setempat, masyarakat dan instansi teknis kehutanan.[32] Berdasarkan teori tersebut kendala dan hambatan dalam kegiatan PHBM pada suatu tempat akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainya, PHBM belum sepenuhnya sesuai dengan konsep awalnya. Yaitu pembagian sharing kayu Dalam sistem PHBM masyarakat desa sekitar hutan yang tergabung dalam sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bernota riil, dimana Lembaga ini akan melakukan kerjasama pengelolaan hutan bersama Perhutani. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan sharing input dari masing-masing pihak. Satu hal yang perlu dicatat dari penerapan sistem ini adalah adanya pembagian hasil kayu dalam pembagian hasil, maka proporsi yang diterima masyarakat 25 persen dan untuk perum perhutani 75 persen harus sesuai dengan perjanjian konsep awalnya dalam sistem ini dimungkinkan pula pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) untuk ikut terlibat dalam pengelolaan hutan. Ani Adiwinata Nawir, Murniati Dkk. kendala dan hambatan PHBM di perum perhutani adalah partisipasi. sekalipun harapan akan partisipasi masyarakat yang lebih besar terus meningkat terdapat berbagai kendala berat yang menghalangi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan PHBM. Terbatasnya keterlibatan masyarakat umumnya dikarenakan ketidak jelasan insentif ekonomi dalam kegiatan PHBM, kurangnya pertimbangan terhadap aspek sosial dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan PHBM, dan tidak cukupnya pembangunan kapasitas organisasi masyarakat sebelum suatu metode teknis diperkenalkan, namun penyebab yang paling pening adalah pemberian kesempatan yang setengah hati kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam mengelola hutan, yang mengakibatkan masalah kepemilikan lahan yang tidak kunjung selesai.[33] Berdasarkan teori diatas kebanyakan kegiatan PHBM kurang memperhatikan aspek ekonomi sebagai bagian dari rancangan dan strategi proyek Perum Perhutani Komponen ekonomi yang penting untuk menjamin keberlangsungan PHBM, yang selama ini masih kurang diperhatikan adalah keberlangsungan PHBM karena tidak adanya mekanisme investasi, analisis kelayakan ekonomi yang memadai dan integrasi pasar yang jelas. Hal tersebut tercermin dalam insentif ekonomi yang tidak jelas yang telah mematahkan semangat masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi secara sukarela. Insentif ekonomi yang jelas sangat penting untuk merangsang partisipasi masyarakat. Hal ini akan diperoleh jika suatu kegiatan PHBM keberlanjutan secara ekonomi dalam jangka panjang, karena adanya keberlanjutan pendapatan masyarakat yang dapat mendudkung kegiatan PHBM.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Seting Lapangan
Penelitian ini mengambil lokasi di RPH Campaka BKPH Sukanagara Utara KPH Cianjur LMDH Wana Suka mekar. Desa Suka mekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur.
Penelitian yang dilakukan di wilayah ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa LMDH wana suka mekar telah berhasil dalam kegiatan PHBM Keberhasilan PHBM tersebut terbukti dengan diberikannya Piagam penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri kehutanan kepada ketua LMDH Wana Suka mekar. yang meraih juara Terbaik II kategori LMDH Perum Perhutani dalam bidang “Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2010”
LMDH wana suka mekar berdiri tahun 2005 berakte notaris No 11 tanggal 11 Mei 2007 mengelola HPD seluas 1.071.08 hektar wilayah kerja RPH Campaka, BKPH Sukanegara Utara, KPH Cianjur, masuk dalam wilayah admnistrasi pemerintahan Kp Ciharum, Ds Sukamekar, Kec Sukanegara, Kab Cianjur.
Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan selama enam bulan, dimulai pada bulan april 2011 sampai dengan bulan september 2011, teknik wawancara yang mendalam disertai studi dokumentasi dan observasi dilakukan secara berulang-ulang selama kurun waktu tersebut agar diperoleh data yang cukup untuk dianalisis, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan laporan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel. 3 Langkah-langkah kegiatan Penelitian
| No | Uraian kegiatan | Bulan | |||||
| April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | ||
| 1 | Penyusunan Dan pengajuan | | | | | | |
| 2 | Penyusunan Pedoman Wawancara | | | | | | |
| 3 | Sidang dan Perbaikan proposal | | | | | | |
| 4 | Observasi awal dan perbaikan proposal | | | | | | |
| 5 | Member check dan pengolahan | | | | | | |
| 6 | Studi dokumentasi | | | | | | |
| 7 | Wawancara tahap satu dan pengolahan | | | | | | |
| 8 | Member check dan pengolahan | | | | | | |
| 9 | Wawancara tahap dua dan pengolahan | | | | | | |
| 10 | Triangulasi dan pengolahan | | | | | | |
| 11 | Penyusunan Bab IV dan Bab V | | | | | | |
| 12 | Sidang Tesis | | | | | | |
Tabel 4: Kode Informan
| No | Informan | Kode |
| 1 | Asper BKPH | AB |
| 2 | Kader PHBM | KP |
| 3 | Kepala Desa | KD |
| 4 | Ketua LMDH | KL |
| 5 | Masyarakat Anggota LMDH 1 | MAL1 |
| 6 | Masyarakat Anggota LMDH 2 | MAL2 |
| 7 | Masyarakat Anggota LMDH 3 | MAL3 |
Berdasarkan pemaparan tabel diatas identitas informan disamarkan, sebagai gantinya digunakan kode informan dalam bentuk abjad kapital. Tujuan pengkodean ini agar lebih memudahkan peneliti dalam memisahkan informasi antara informan yang satu dengan yang lain.
Subjek dalam penelitian ini yang dijadikan informan utama adalah Kader PHBM (Tatang Efendi) informan Pendukung Asper BKPH (Yusuf S) triangulasi Ketua LMDH (A Juhana), Kepala Desa (Maman Sulaeman) dan Masyarakat Anggota LMDH MAL1, MAL2, MAL3 dan seterusnya.
Tabel 5 : Kode Pertanyaan
| No | Sub Fokus | Pertanyaan | Kode |
| 1 | 1 | 1 2 | A1 A2 |
| 2 | 2 | 1 2 3 4 | B1 B2 B3 B4 |
| 3 | 3 | 1 2 3 | C1 C2 C3 |
| 4 | 4 | 1 2 3 | D1 D2 D3 |
B. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan beberapa pertimbangan, antara lain :
a. Menurut S.Nasution, apabila peneliti ingin mengetahui bagaimana macam-macam orang memandang realitas, misalnya mengenai dikeluarkannya peraturan baru, atau bila peneliti ingin mempelajari sesuatu kasus, atau penelitian yang mempunyai sample kecil, yang serasi adalah metode penelitian kualitatif.
b. Menurut Lexy. J. Moleong, bahwa metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
Berdasarkan teori diatas bahwa penelitian ini pada umumnya memiliki tujuan untuk menemukan kejelasan dari suatu objek yang diteliti. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis maupun teori tertentu, namun merupakan suatu upaya menampilkan peran partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan melalui kegiatan PHBM di Perum Perhutani RPH Campaka Kabupaten Cianjur[34]
Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naturalistik, artinya mengamati secara cermat kejadian-kejadian yang berlangsung secara alamiah atau tanpa control, sehingga hasil penelitian ini dapat memaparkan secara jelas tentang peran partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan melalui kegiatan PHBM di Perum Perhutani.
C. Data dan Sumber Data
1. Data penelitian
Sesuai dengan fokus penelitian, pengumpulan Data primer diperoleh dari hasil observasi di lapangan dengan berdiskusi secara langsung dengan informan. Penggarap, kelompok tani hutan, buruh tani dan penyadap getah pinus adalah sumber data utama secara langsung dapat diperoleh keterangannya, terutama berkaitan dengan aktifitas perecanaan pembibitan, penanaman dan pemanenan pohon hutan, komoditi tanaman semusim, dan lokasi/petak penanaman. Data kelembagaan dan rencana kerja kelompok dapat diperoleh melalui ketua lembaga masyarakat desa hutan (LMDH)
Data sekunder diperoleh dari KPH Cianjur dan BKPH Sukanagara Utara dan dari Desa Sukamekar. langkah-langkah kegiatan penelitian dengan mengharapkan memperoleh informasi data yang akurat sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan persiapan dan tahap pelaksanaan. Setelah menyelesaikan perijinan, langkah berikutnya adalah
1. Tahap Orientasi: Pada tahapan ini, melakukan kunjungan beberapa hari yang direncanakan sebagai langkah awal dalam memperoleh gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan melalui kegiatan PHBM di Perum Perhutani, setelah diketahui bahwa focus penelitian, dengan demikian kesiapan orientasi ditujukan untuk mengamati bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan melalui kegiatan PHBM di Perum Perhutani.
2. Tahapan Eksplorasi: Tahap ini merupakan kegiatan penelitian yang sesungguhnya yaitu melakukan pengumpulan data sesuai dengan focus penelitian. Pada tahap ini disediakan waktu untuk menyusun petunjuk dalam memperoleh data, seperti petunjuk wawancara dan pengamatan agar pembaca tidak menyimpang dari konteks fokus penelitian. Setelah petunjuk atau pedoman dibuat, dilakukan wawancara langsung dengan sumber yang memiliki keterkaitan dengan subyek penelitian. Dilanjutkan dengan melakukan observasi dan dokumentasi untuk menambah kelancaran kegiatan ini dengan perlengkapan buku catatan, kamera dan alat perekam.
3. Tahap Member Check: tahap ini melakukan analisis data dan menuangkan dalam bentuk laporan, setelah laporan dibuat, maka pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data untuk menghindari ketidaksesuaian dengan kenyataan. Pengecekan ini dilakukan terhadap nara sumber yang relevan untuk mengkonfirmasikan catatan, data dari hasilo wawancara serta menyimpulkannya bersama informan. Waktu member check bersamaan dengan tahap eksplorasi, hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengoreksi catatan hasil wawancara atau temuan lainnya.
D. Prosedur pengumpulan/perekaman data
Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil observasi dan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber informan di lapangan. Informan yang dipilih untuk mengetahui proses partisipasi dimulai petani penggarap atau pesanggem, penyadap getah pinus anggota LMDH. Data-data tentang Partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan melalui kegiatan PHBM di perum perhutani RPH Campaka kabupaten Cianjur dikumpulkan dari Petugas KRPH (Bpk. Yusuf S) ,Kader PHBM (Bpk.Tatang Efendi) dan ketua LMDH (Bpk. A Juhana) dan Kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan PHBM
Pengumpulan informasi dan data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran data di pemerintah desa dan kecamatan, serta administrasi di BKPH Sukanagara Utara dan Asper BKPH Campaka Utara. Penentuan responden, khususnya di tingkat masyarakat desa hutan menggunakan metode Pada studi ini menetapkan sampel secara purposive dengan memilih 3 orang subjek, bukan menimbang tentang proporsi yang represintatif, melainkan menimbang bahwa subjek tersebut akan menyumbangkan data dalam pengembangan teori sesuai fokus penelitian. Tujuan pengambilan sampel tersebut dimaksudkan agar hasil penelitian memiliki komparabilitas, yakni dapat diperbandingkan atau dapat diterjemahkan pada kasus-kasus hasil penelitian lainnya, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi pembanding untuk melakukan sesuatu yang sama baiknya atau lebih baik dari hasil penelitian ini. Untuk data selanjutnya atau informan pendamping diperoleh dengan cara snowball throwing.
Teknik pengkodean dalam pengumpulan data lapangan diperlukan untuk mempermudah pembuatan catatan lapangan, format wawancara, dan data-data lain terkait pemetaan dan dokumentasi.
1. Observasi, Peneliti melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian, yaitu di RPH.Campaka Kabupaten Cianjur dan mencatat hal-hal yang diperlukan sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara.
2. Wawancara: Peneliti menggunakan teknik ini dalam menggali informasi dari Petugas BKPH setempat, dan Ketua LMDH dengan cara berkomunikasi lisan atau tatap muka. Melalui wawancara ini diharapkan agar dapat menungkapkan kesesuaian data dilapangan
3. Studi Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai informasi untuk memeriksa, meneliti dokumen-dokumen seperti; perencanaan program, langkah-langkah pelaksanaan, serta catatan lainnya yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan melalui kegiatan PHBM di Perum Perhutani RPH Campaka Kabupaten Cianjur
4. Studi Kepustakaan, Peneliti mencari informasi dari beberapa narasumber bahan tulisan atau referensi lainnya yang berkaitan dengan subyek penelitian dari masalah yang akan diteliti.
Dalam mendukung tehnik pengumpulan data ini, maka akan digunakan persiapan peralatan pendukung seperti peralatan menulis, tape recorder, camera foto dengan maksud supaya keakuratan dan kelengkapan informasi lebih menjamin.
E. Pengecekan keabsahan Data
Menguji keabsahan data yang berhasil dikumpulkan, maka perlu dilakukan validitas data melalui metode triangulasi. Triangulasi data dilakukan dengan cara mewawancarai sumber lain, yaitu Masyarakat sekitar Perum Perhutani. Tahap ini dilakukan setiap selesai melakukan wawancara dan observasi, dengan mengkonfirmasikan kembali catatan lapangan yang telah diperoleh.
F. Teknik Analisis Data
Teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif analitik ini, dimulai dengan menganalisa data serta mengadakan interpretasi sebagai persiapan menghadapi masalah yang akan terjadi, namun demikian tahapan berikutnya tetap dilakukan yaitu mereduksi data, mengklasifikasikan data, menyajikan data, memverifikasi data dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.
Mereduksi adalah melakukan penyortiran terhadap data mentah untuk dipilih dan dirangkum sehingga mempermudah penganalisaan. Menyajikan data adalah pelaporan disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas. Menyajikan data adalah pelaporan dari data sebelumnya yang disusun secara sistematis sebagai gambaran yang jelas. Pada tahap verifikasi data yaitu, melakukan langkah pembuktian agar keabsahan data dapat dijamin keasliannya. Untuk mengetahui validitas data, maka data tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut;
a. Drajat kepercayaan
b. Keteralihan
c. Ketergantungan
d. Kepastian
Mengembangkan ketergantungan, dengan secara cermat melakukan pengecekan secukupnya terhadap laporan agar tidak menyimpang, salah, atau keliru. Dalam mencapai kepastian dilakukan pemeriksaan ulang beberapa kali sebagai konfirmasi dalam meyakinkan paparan yang nyata.
Tingkat validitas data hasil penelitian harus memenuhi ketentuan yang ada yaitu:
a. Kriteria derajat kepercayaan (credibility) pemeriksaan datanya dilakukan dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan atau diskusi sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota.
b. Keteralihan (transferability) peneliti membekali diri dengan pengetahuan secukupnya tentang masalah yang diteliti dengan cara membanyak buku referensi dan bertanya langsung kepada orang-orang yang memahami mengenai Pengelolaan Hutan Sumberdaya Bersama Masyarakat (PHBM)
c. Kebergantungan (dependability) peneliti melakukan auditing untuk mengecek laporan agar tidak melenceng, keliru atau salah.
d. Dan Kepastian (confirmability) peneliti melakukan pemeriksaan ulang sebagai konfirmasi untuk meyakinkan bahwa laporan yang dipaparkan sesuai dengan kenyataan.
G. Tahapan-tahapan Penelitian
Tahap pertama penelitian ini adalah pengamatan lapangan dengan menelaah kepustakaan dengan mengekplorasi teori-teori berdasarkan pengamatan lapangan keduanya masuk kedalam tahap orientasi penelitian. Penelaahan pustaka dan observasi dilakukan untuk memutuskan fokus penelitiannnya yaitu Partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan di sekitar perum Perhutani RPH Campaka Kabupaten Cianjur, selanjutnya adalah menyajikan data pada tahap pertama dan kedua secara sistematis.
Tahap-tahap penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
| Telaah Kepustakaan |
| Pengamatan Lapangan |
| Focus masalah penelitian |
| Member Check |
| Triangulasi |
Dokumentasi
| Penarikan Kesimpulan |
| Analisis Data Selama pengumpulan data Setelah pengumpulan data Penyajian dat |
| Antar Situs |
| Dalam Situs |
| Analisis Pasca pengumpulan Data Pengkategorian data Pengkodean data Penyortiran data Penyajian data Hasil analisis data Dalam situs dan antar situs |
Gambar 3.2 Tahapan-tahapan Penelitian
Sumber: Bahan Buku metodologi penelitian[35]
DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho, W. C.. I N. N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, labueni Siboro. Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Bogor : Wtlands International-IP, 2004
Arief Arifin. Hutan & Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
A Rofiq, Widodo R. B. Pemberdayaan Pesantren. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2005.
Abdulkarim Aim. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
Hendar, Kusnadi. Ekonomi Koperasi. Jakarta: Lembaga penerbit FE-UI, 2002.
Harsono Y, Rubiyanto P.A. ,Purbocahyono Dedi Y, K M.G. Suwarni, Astuti C. Wiganti Retno, Mudayen Y.M.V, Indra Darmawan. Menatap Masa Depan. Yogyakarta : PT. Pustaka Widyatama, 2006.
Leeuwis Cees. Komunikasi Untuk Inovasi Pedesaan. Yogyakata : Kanisius, 2009.
LIPI. Komunika. Jakarta : Lipi Press, 2006
Murtono Sri, Suryono Hassan, Martiyon. Pendidikan Kewarganegaraan. Bogor: Penerbit Quadra, 2007.
Munggoro Dani Wahyu. Hutan Kemasyarakatan. Jakarta: Pustaka Latin, 2004.
Nawir Ani Adiwinata, Murniati, Rumboko Lukas. Rehabilitasi Hutan di Indonesia. Bogor : CIFOR, 2008.
Nasution Muslimin. Sistem Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Sajadah Net, 2001.
Naja, Rahman Hasanuddin. Membangun Micro Banking. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
Patlis M. Jason. Pedoman Umum Penyusunan Peraturan Daerah. Bogor : CIFOR, 2004
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2009
Sumawinata Sarbini. Politik Ekonomi Kerakyatan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004
Sumardi, S.M. Widyastuti. Dasar-dasar perlindungan hutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
Suratmo Gunarwan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004.
Sutanto Rachman.Penerapan Pertanian Organik. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
Soeroso Santoso. Mengutamakan Pembangunan Berawasan Kependudukan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2005.
Tangkilisan Hessel Nogi S. Manajemen Publik. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 2007.
Triwamwoto Petrus Citra. Kewarganegaraan. Bogor: Penerbit Grasindo, 2007.
Wulan Yuliana Cahya, Yasmi Yurdi, Dkk. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia. Bogor : CIFOR, 2004.
Wanggai Frans. Manejemen Hutan. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
Wrihantolo R. Randy, Dwidjowijoto Riant Nugroho. Manajemen Pemberdayaan. Jakarta : PT. Gramedia, 2007.
Widianto, Wijayanto Nurheni, Didik Suprayogo. Pengelolaan dan Pengembangan Agrofororestri. Bogor : ICRAF, 2003
_______Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi. Jakarta: Penerbit CV. Mitra Usaha Tanyo, 2004.
_______Strategi Pemberdayaan Masyarakat di era Globalisasi. Bogor: Penerbit Indomedia, 2007.
INSTRUMEN WAWANCARA
A. upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam meningkatkan partisispasi masyarakat dalam pengembangan agroforestri?
a. Peneliti : Bagaiman aktifitas harian/kelompok masyarakat yang terlibat?
b. Peneliti : Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan di Perum Perhutani?
B. Pemberdayaan dalam kegiatan PHBM
a. Peneliti : Cara-cara apa yang dilakukan masyarakat dalam melestarikan sumberdaya alam hutan?
b. Peneliti : Tanaman apa saja yang ditanam oleh masyarakat dalam melestarikan hutan?
c. Peneliti : Bagaimana tanggung jawab kelompok/lembaga terkait dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan?
d. Peneliti : Pelatihan, kursus dan ceramah apa saja yang terkait dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan?
C. Pembinaan dan Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh Perum Perhutani
a. Peneliti : Bagaimana kontribusi Perum Perhutani dalam bidang penyerapan Tenaga Kerja?
b. Peneliti : Kegiatan apa saja selain PHBM yang dilakukan oleh Perum Perhutani dalam pengembangan ekonomi kerakyatan?
c. Peneliti : Berapa orang yang di pekerjakan oleh Perum Perhutani?
D. Upaya yang dilakukan Perum Perhutani dalam mengatasi Kendala dan Hambatan dalam kegiatan PHBM?
a. Bagaimana upaya yang dilakukan apabila metode yang digunakan tidak berjala lancar?
b. Kendala dan hambatan apa saja yang ditemui dalam kegiatan PHBM ?
c. Bagaimana peran forum komunikasi yang ada di dalam masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada?
Data Tambahan Recorder (Ketua LMDH)
a. Bagaimana bapak memberdayakan masyarakat desa hutan khususnya dalam usaha tani?
b. Bagaimana bapak mengamankan hutan agar terhindar dari pencurian?
c. Bagaimana lembaga ini bisa tetap eksis?
d. Bagaimana bapak meningkatkan partisipasi dan bagaimana bapak mengelola lembaga LMDH ini agar tetap eksis?
e. Bagaimana bapak mengelola desa hutan?
f. Bagaimana bapak memberdayakan masyarakat agar pendapatan meningkat dan hutan tetap lestari?
g. Bagaimana LMDH terus berkontribusi unuk melestarikan hutan?
h. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam kegiatan perlindungan tanaman terhaap tanaman areal PHBM?
i. Kapankah program PHBM mulai dikenalkan pada masyarakat?
j. Sejak kapankah Bapak/Ibu mengikuti program PHBM?
k. Apakah Perum Perhutani melibatkan semua masyarakat dalam pengelolaan program PHBM?
l. Apakah dalam pengenalan program tersebut masyarakat desa memberikan masukan atau saran?
m. Dimanakah dilakukan pengenalan program PHBM?
n. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam pengembangan hutan rakyat?
o. Apakah Bapak/ibu terlibat dalam kegiatan pengembangan hutan rakyat? Jika ya, apa yang saudara lakukan?
p. Adakah penjagaan khusus oleh masyarakat untuk menjaga keamanan tanaman areal hutan?
Jika ya, kapankah penjagaan itu dilakukan?
q. Apa yang masyarakat lakukan untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan?
r. Apakah Bapak/Ibu merasakan hasil dari pelaksanaan Program PHBM? Jika ya, hasil apa yang Bapak/Ibu rasakan?
Informan dari ( BKPH )
1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi?
2. Menurut Bapak apakah dengan adanya kegiatan PHBMdapat menyerap tenaga kerja? Berapa banyak menyerap tenaga kerja? Dan bagaimana peran gender untuk meningkatkan pendapatan?
3. Sumberdaya alam apa saja yang dimanfaatkan dan bagaimana pemanfaatannya?
4. Tata cara tradisional/lokal apa saja yang mampu melestarikan sumberdaya alam?
5. Bagaimana tanggungjawab kelompok/lembaga terkait dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan?
6. Pelestarian, kursus dan ceramah apa saja terkait pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan?
Catatan Perekaman Data Tambahan Melalui Tape Recorder ( Dari Masyarakat Anggota LMDH )
1. Bagaimana Bapak bisa memberdayakan masyarakat desa hutan khususnya dalam usaha tani?
2. Bagaimana Bapak mengamankan hutan agar terhindar dari pencurian?
3. Bagaimana lembaga LMDH ini tetap eksis?
4. Bagaimana Bapak mengelola desa hutan?
5. Bagaimana Bapak memberdayakan masyarakat agar pendapatan meningkat dan hutan tetap Lestari?
6. Bagaimana lembaga LMDH terus benkontribusi untuk melestarikan hutan?
7. Tanaman apa yang penting untk pelestarikan hutan?
a. Petani dapat bagian sadapan?
b. Terkait tanaman pengisi apa itu artinya?
c. Tanaman apa saja?
d. Tanaman itu ditanam dimana?
e. Bagaimana Bapak mengajak?
f. Ada Berapa anggotanya?
g. Dimana membuat pupuknya?
h. Ada koordinasi PNPM Mandiri khususnya koordinasi otomatis antar kecamatan dan LMDH?
[1] Hendar dan Kusnadi, Ekonomi Koperasi. ( Jakarta : Lembaga penerbit FE-UI, 2002),p.73.
[2] Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik. (Jakarta : Gramedia 2007).p.321.
[3] Ibid. p.322.
[4] Ibid. p.321.
[5] Cees Leeuwis. Komunikasi Untuk Inovasi edesaan. (Jogjakarta : Kanisius, 2009).p.405.
Gambut. (Bogor : Wtlands International, 2004).p.49.
[7] Petrus Citra Triwamwoto. Kewarganegaraan. (Jakarta : Grasindo, 2004).p.61
2007).p.50.
[9] Arifin Arief. Hutan & Kehutanan. (Yogyakarta : Kanisius, 2001).p.87.
[10] Ibid, p.87.
[11] Frans Wanggai. Manajemen Hutan. (Jakarta : Grasindo, 2009).p.25.
[12] LIPPI. Komunika. (Jakarta : Lippi Press, 2006),p.47.
[13] Ibid. p.48
[14] Randy R. Wrihantolo. Manajemen Pemberdayaan. (Jakarta : Gramedia, 2007).p. 179.
[15] I bid, 179
[16] Ibid, 180
[17] Rafiq A. Pemberdayaan Pesantren. (Jakarta : Pustaka Pesantren, 2005).P.34.
[18] J.Kaloh. Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi. (Bogor : Indomedia,
2004).p.255.
[19] Dadan Mulyana, Ceng asmarahman. 7 Jenis ka penghasil rupiah. (Jakarta : Agromedia Pustaka, 2010), p.8.
[20] Karwan A. Salikin. Sistem Pertanian Berkelanjutan. (Yogyakarta : Kanisius, 2003).p.66.
[21] H De Foresta, A Kusworo, G Michigan dan WA Djatmiko. Agroforest Khas Indonesia. (Bogor : Penerbit Grafika Desa Putera, 2000).p.1
[22] Widianto, Nurheni Wijayanto, dan Didik Suprayogo. Pengelolaan dan Pengembangan Agroforestri. ( Bogor : ICRAF, 2003).p.9.
[23] Mohamad Soerjani. Kebijakan Lingkungan Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan
Agroforestri. (Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan,2007).p.34.
[24] Widianto, Nurheni Wijayanto, dan Didik Suprayogo. Pengelolaan dan Pengembangan Agroforestri. ( Bogor : ICRAF, 2003).p.9.
[25] Y. Harsono. Menatap Masa Depan. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006).p.137.
[26] Gunawan Sumodiningrat & Riant Nugroho. Membangun Indonesia Emas. (Jakarta : Pustaka Gramedia, 2005).p.159.
[27] Sarbini Sumawinata. Politik Ekonomi Kerakyatan. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004).p.240.
[28] Muslimin Nasution. Sistem Ekonomi Kerakyatan kerangka Pemikiran dan Implementasi. (Jakarta: Sajadah Net, 2001),p. 63.
[29] Hasanudin Rahman, Naja. Membangun Micro Banking. (Yogyakarta : Pustaka Widyatama,
2004).p.2.
[30] Ibid, p. 66.
[31] Yuliana Cahya Wulan, Yurdi Yasmi, Christian Purba, Eva Wollenberg. Analisa Konflik sektor kehutanan di indonesia. (Bogor : Center for international forestry research CIFOR, 2004).p.48.
[32] Ibid. 98
[33] Ibid. 104
Langganan:
Postingan (Atom)


